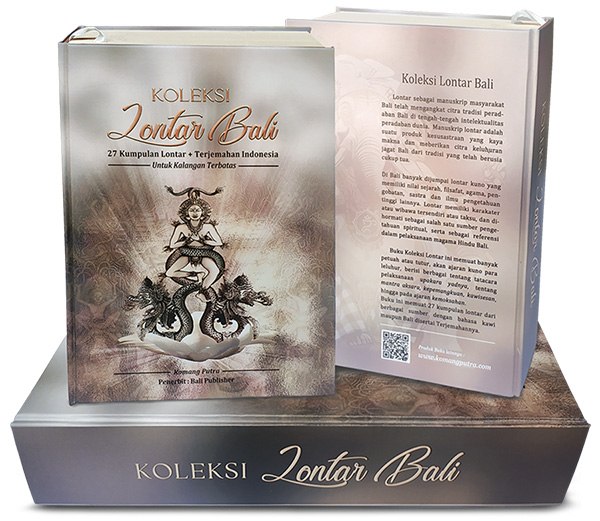Sapuh Leger berasal dari kata dasar “sapuh” dan “leger”. Dalam kamus Bali-Indonesia, terdapat kata sapuh yang artinya membersihkan, dan kata leger sinonim dengan kata leget (bahasa jawa) yang artinya tercemar atau kotor. Sehingga secara etimologi sapuh leger diartikan pembersihan atau penyucian dari keadaan tercemar atau kotor.
Kata “Sapuh Leger” di Bali secara khusus dihubungkan dengan pertunjukkan wayang dalam kaitannya untuk pemurnian kepada anak/orang yang lahir tepat pada wuku wayang dalam siklus kalender tradisional Bali. Secara ritual upacara pemurnian dinamakan lukat/nglukat atau penglukatan, yaitu suatu aktivitas untuk membuat air suci (tirta) yang dilakukan baik oleh seorang pendeta (pedanda/pemangku) maupun seorang dalang (Mangku Dalang) dengan tujuan untuk membersihkan mala (kekotoran) rohani seseorang. Secara keseluruhan, wayang sapuh leger adalah suatu drama ritual dengan sarana pertunjukkan wayang kulit yang bertujuan untuk pembersihan atau penyucian diri seseorang akibat tercemar atau kotor secara rohani.
Secara tradisi pertunjukkan wayang sapuh leger merupakan suatu peninggalan budaya kehidupan masyarakat Bali yang diadatkan dan dianggap sakral, maka ia termasuk wali (bagian upacara) diselenggarakan untuk upacara keagamaan (manusia yajna) yaitu untuk anak/orang yang lahir pada wuku wayang. Pertunjukkan ini berfungsi sebagai inisiasi, merupakan salah satu upacara ritus yang menyangkut keselamatan kehidupan umat manusia pendukung budaya tersebut. Hal ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dalam perilaku kehidupan social masyarakat Bali, dengan peristiwa tetap secara periodik, berulang tiap-tiap 6 bulan (210 hari) menurut perhitungan kalender Bali atau 7 bulan Masehi.
Dalam Cerita Wayang Lakon Sapuh Leger, diceritakan Dewa Kala akan memakan segala yang lahir pada wuku wayang (menurut kalender Bali) atau yang berjalan tengah hari tepat wuku wayang. Atas petunjuk ayahandanya Dewa Siwa, Dewa Kala mengetahui bahwa Dewa Rare Kumara putra bungsu dari Dewa Siwa lahir pada wuku wayang.
Pada suatu hari bertepatan pada wuku wayang, Dewa Rare Kumara dikejar oleh Dewa Kala hendak dimakannya. Dewa Rare Kumara lari kesana ke mari menghindarkan dirinya dari tangkapan Dewa Kala. Ketika tengah hari tepat tepat pada wuku wayang, dan dalam keadaan terengah-engah kepayahan Dewa Rare Kumara nyaris tertangkap Bhatara Kala kalau tidak dihalangi oleh Dewa Siwa. Oleh karena dihalangi oleh Dewa Siwa maka Dewa Kala hendak memakan ayahandanya (Siwa). Hal ini menyebabkan Dewa Siwa berjalan tengah hari tepat pada wuku wayang.
Diceritakan selanjutnya, Dewa Siwa rela dimakan oleh putranya Dewa Kala, dengan syarat Bhatara Kala dapat menterjemahkan dan menerka ini serangkuman sloka yang diucapkan Dewa Siwa. Bunyi sloka tersebut :
Om asta pada sad lungayan,
Catur puto dwi puruso,
Eko bhago muka enggul,
Dwi crengi sapto locanam
Dewa Kala segera menterjemahkan sloka itu serta menerka maksudnya ;
Om asta pada: Dewa Siwa dengan kaki delapan, yaitu kaki Dewa Siwa enam kaki, Dewi Uma dua, semuanya delapan.
Sad Lungayan: Tangan enam yaitu tangan Dewa Siwa empat, tangan Dewi Uma dua semua enam.
Catur puto: Buah kelamin laki-laki empat, yaitu buah kelamin Dewa Siwa Dua, buah kelamin lembu dua,semuanya empat.
Dwi puruso: Dua kelamin laki-laki, yaitu kelamin Dewa Siwa satu, kelamin lembu satu, semuanya dua.
Eka bhago: Satu kelamin perempuan yaitu kelamin Dewi Uma.
Dwi crengi : Dua tanduk yaitu tanduk lembu.
Sapto locanam, tujuh mata yaitu mata Dewa Siwa dua, mata Dewi Uma dua, mata lembu dua, yaitu hanya enam mata tidak tujuh.
mana lagi saya tidak tahu… kata Dewa Kala.
Dewa Siwa kemudian bersabda:
Mataku tiga (Tri Netra), diantara keningku ada satu mata lagi, mata gaib yang dapat melihat seluruh alam ditutup dengan cudamani.
Akhirnya Dewa Kala tidak dapat menerka dengan sempurna sloka itu, oleh karena matahari sudah condong kebarat, maka Dewa Kala tidak berhak memakan Dewa Siwa ayahandanya. Karena itu Dewa Kala meneruskan pengejaran kepada Dewa Rare Kumara yang telah jauh larinya masuk ke halaman rumah-rumah orang.